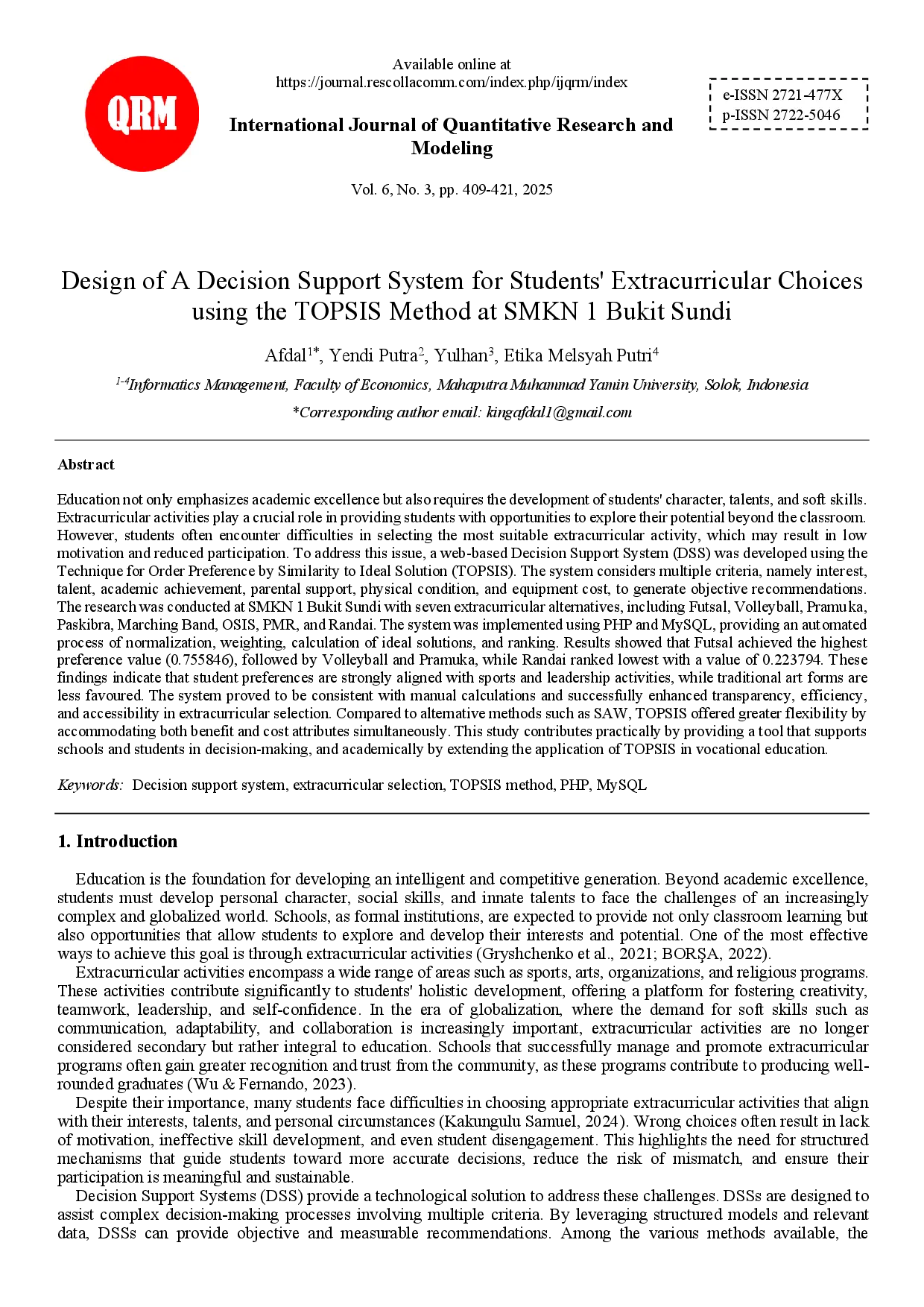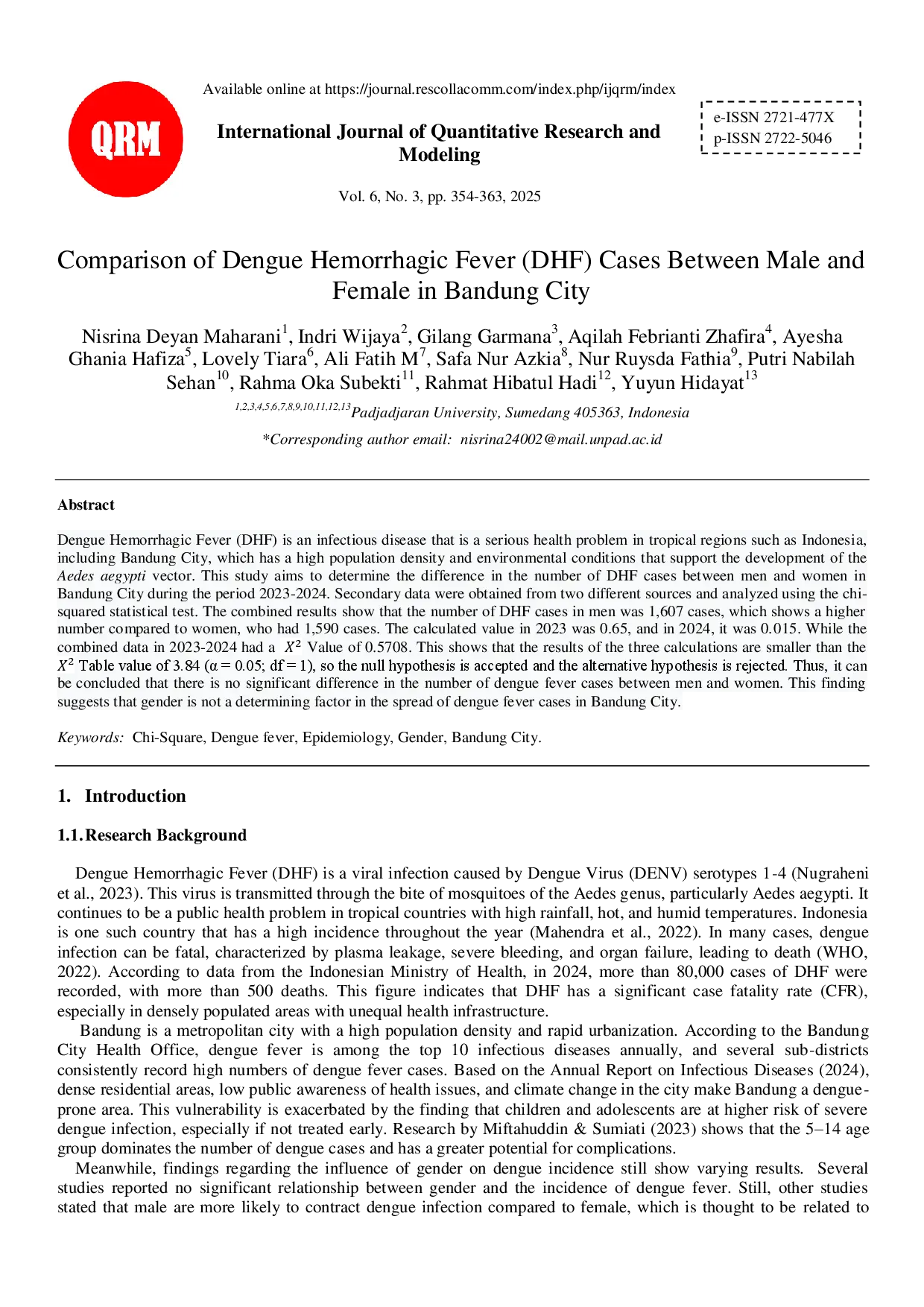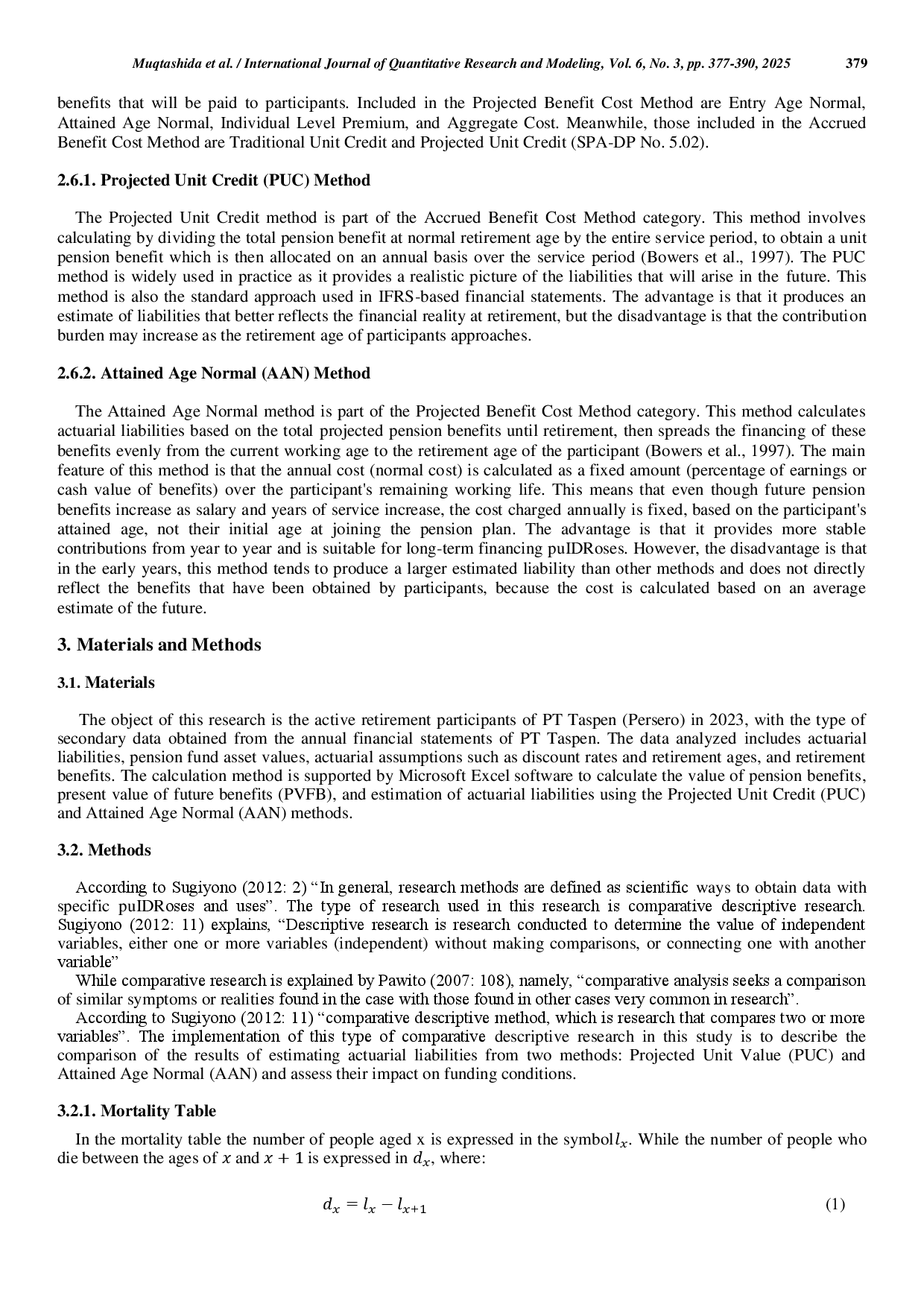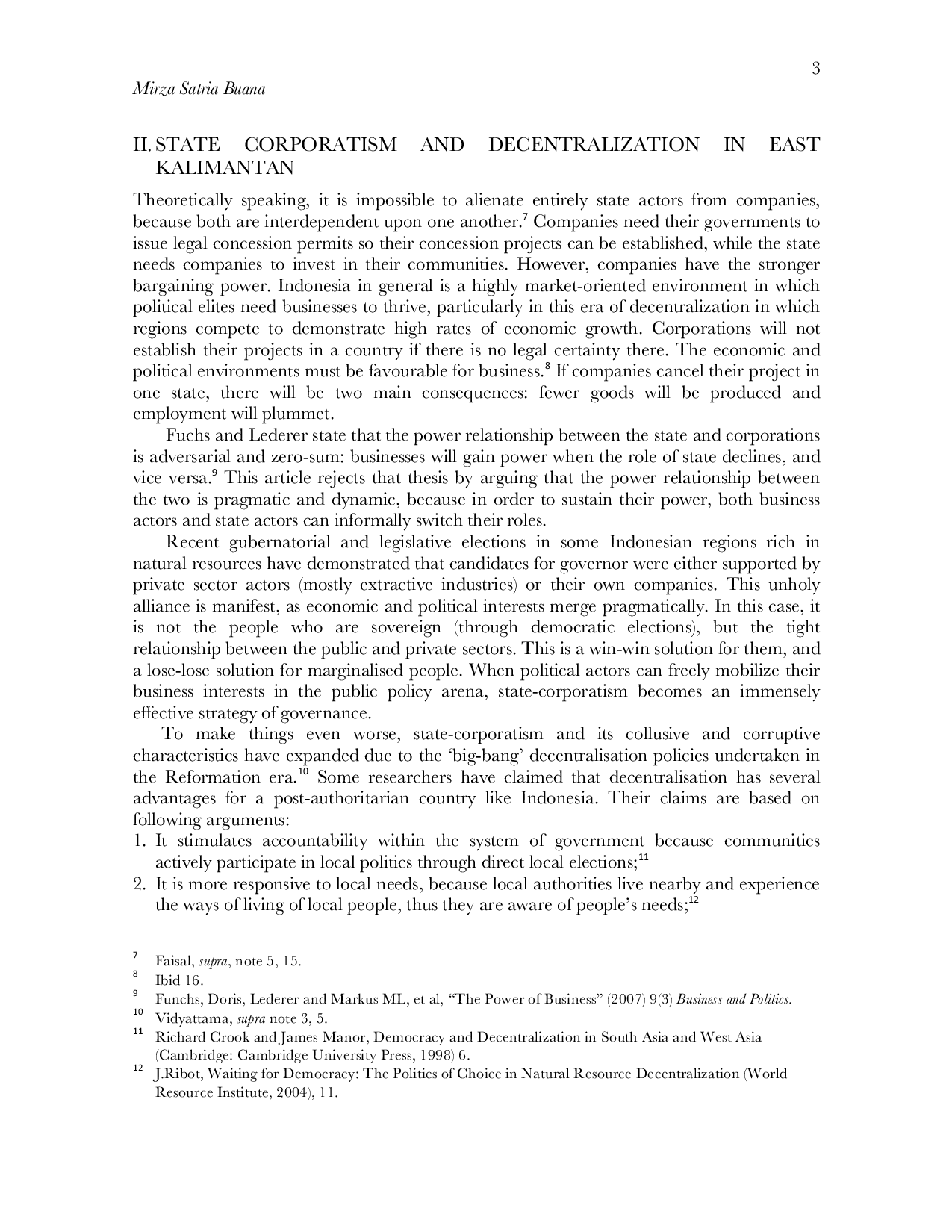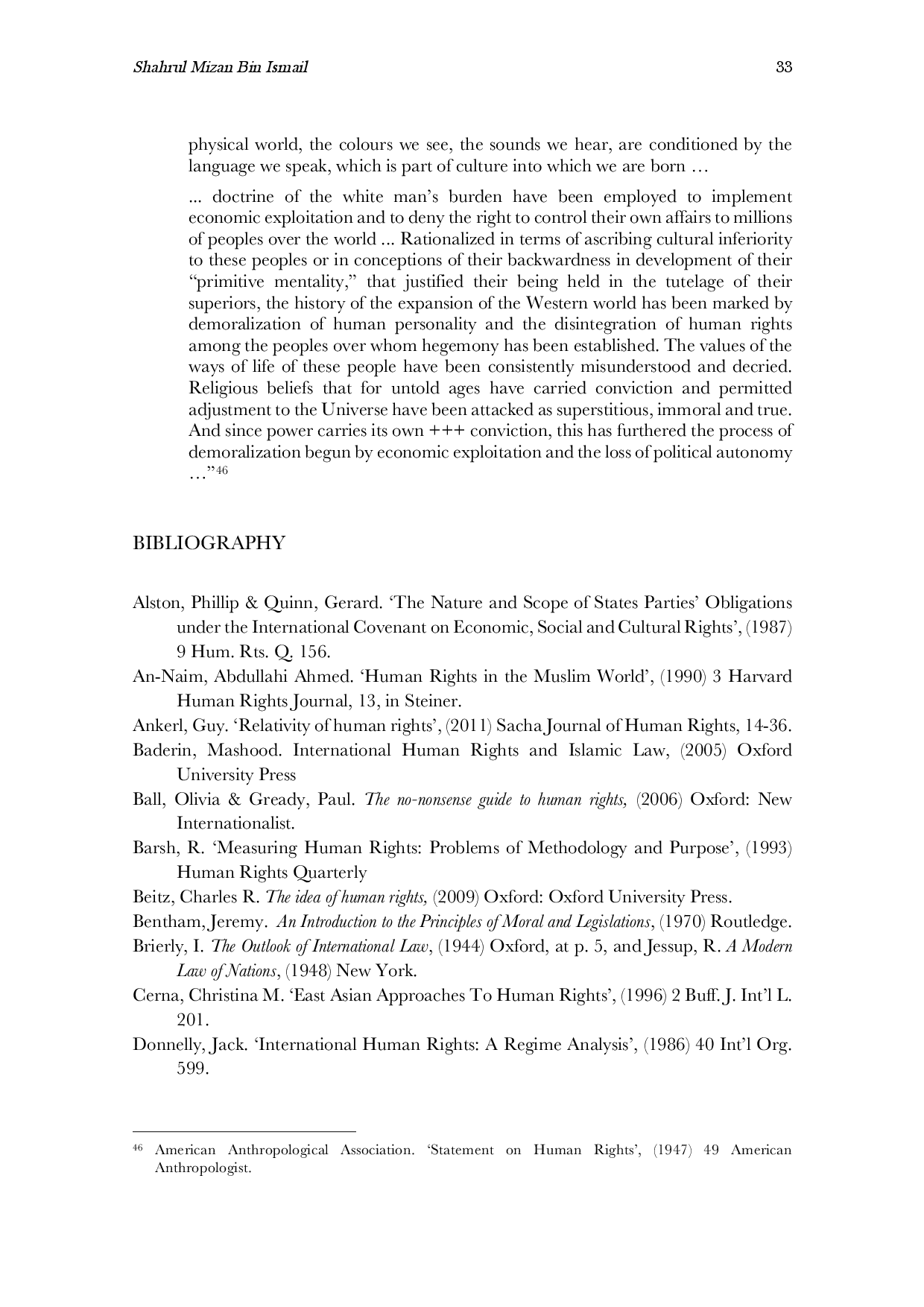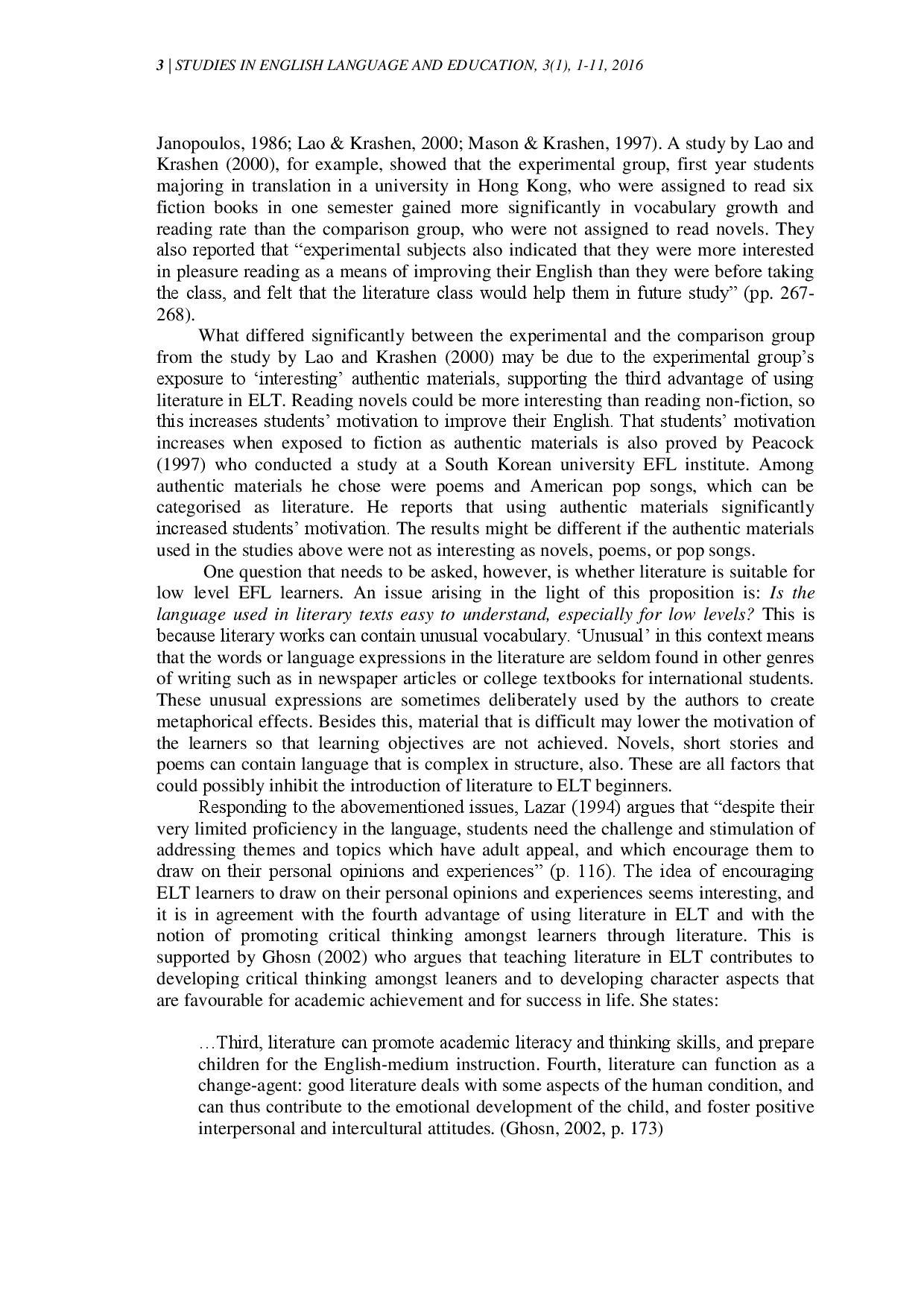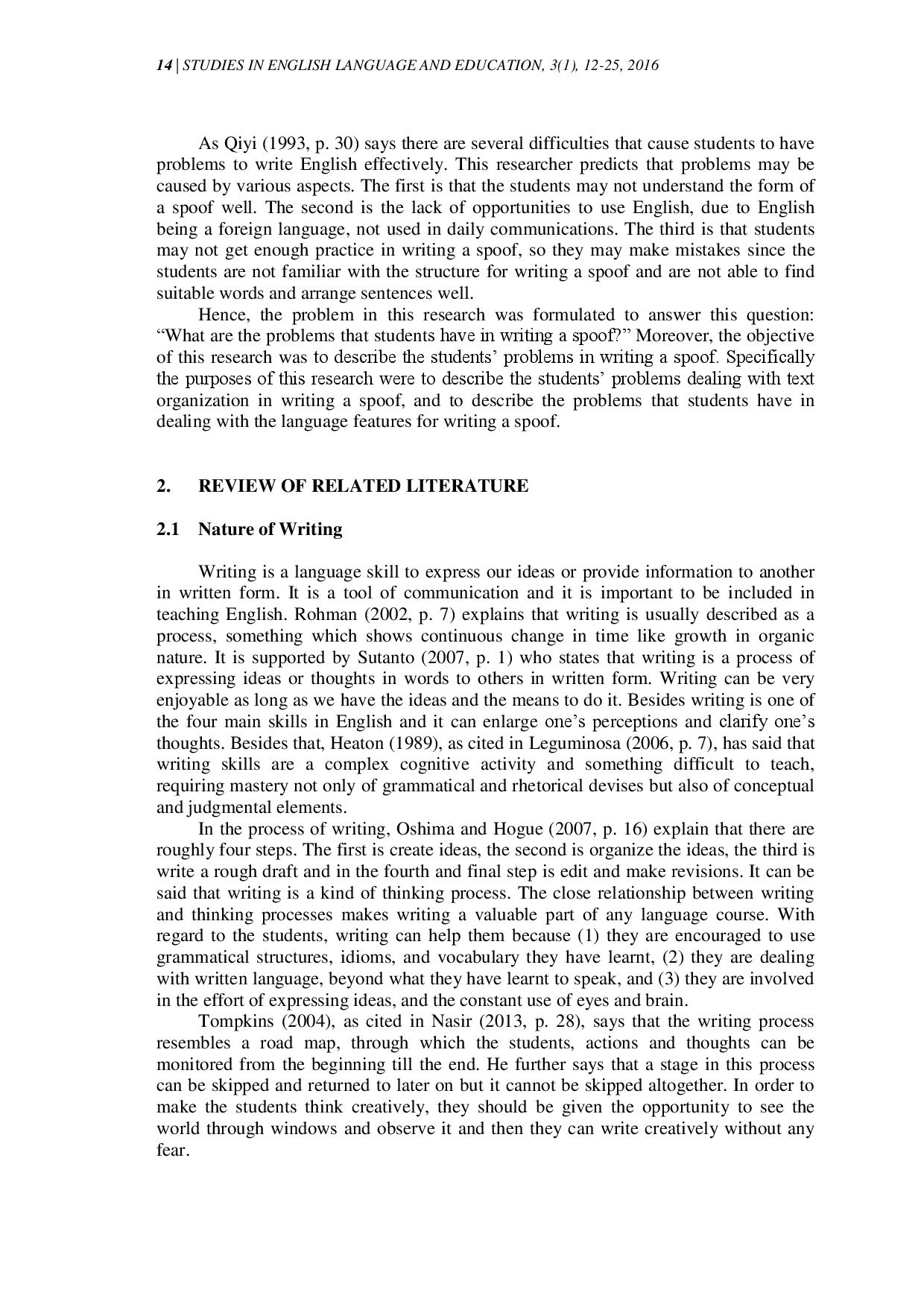UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsTransisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum, kekerasan fisik, kriminalisasi jenis-jenis jurnalisme tertentu, dan kurangnya dukungan dari lembaga peradilan menciptakan suasana berbahaya bagi para jurnalis dan menghambat proses jurnalistik. Dalam model desentralisasi ini, kekerasan terhadap jurnalis sering kali dilakukan oleh anggota organisasi politik daerah dan lokal, bukan agen pemerintah nasional. Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan, pengadilan itu sendiri telah digunakan sebagai alat untuk sensor media, membungkam oposisi, dan mengintimidasi awak media. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga media yang beroperasi dengan standar profesionalisme jurnalistik dan berupaya menghasilkan berita jujur dan tidak bias adalah yang paling sering menjadi sasaran gugatan dan tuntutan kriminal yang tidak adil. Artikel ini juga menggambarkan konfigurasi baru kekuasaan politik yang menggabungkan kebebasan pers, kepemilikan dominan atas media, dan konteks demokrasi illiberal yang membentuk kebebasan pers di Indonesia.
Pada awal masa pasca-Suharto, terutama di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebebasan pers mencapai puncaknya dengan dibubarkannya Departemen Informasi dan diberlakukannya Undang-Undang Pers 1999 yang memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan berekspresi.Namun, di bawah pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, kebebasan pers mengalami kemunduran akibat penyalahgunaan hukum pidana, munculnya undang-undang yang membatasi kebebasan pers, serta meningkatnya kekerasan fisik dan gugatan hukum tidak adil terhadap jurnalis oleh aktor non-negara.Meskipun terdapat kemajuan struktural, tantangan sistemik seperti impunitas, pengaruh elit lokal, dan lemahnya penegakan hukum terus mengancam kebebasan pers, sehingga reformasi hukum lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme mediasi oleh Dewan Pers yang dianggap sebagai solusi damai justru menghalangi proses hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan apakah model ini secara tidak sengaja memperkuat impunitas. Selain itu, perlu diteliti bagaimana penggunaan UU ITE dan UU Pornografi secara selektif terhadap jurnalis independen berbeda dari penerapannya terhadap warga biasa, dan apakah ada pola sistematis dalam menargetkan media yang mengungkap korupsi daerah. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak ekonomi dari gugatan ULAP (Unjustifiable Lawsuits Against the Press) terhadap kelangsungan media lokal, termasuk bagaimana biaya hukum yang tinggi dan ancaman kebangkrutan memaksa redaksi untuk melakukan sensor diri, serta bagaimana media alternatif berbasis komunitas dapat mengisi ruang informasi yang ditinggalkan akibat tekanan hukum dan kekerasan. Dengan memahami ketiga dimensi ini—mekanisme penyelesaian sengketa, penyalahgunaan hukum, dan tekanan ekonomi—penelitian ini akan memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebebasan pers di Indonesia secara perlahan terkikis bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan lokal, finansial, dan hukum yang saling terkait.
| File size | 593.87 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Futsal menjadi kegiatan ekstrakurikuler paling direkomendasikan dengan nilai preferensi tertinggi, diikuti oleh Bola Voli dan Pramuka, sedangkan RandaiFutsal menjadi kegiatan ekstrakurikuler paling direkomendasikan dengan nilai preferensi tertinggi, diikuti oleh Bola Voli dan Pramuka, sedangkan Randai
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah kasus demam berdarah antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini menunjukkanDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah kasus demam berdarah antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini menunjukkan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Through this analysis, it is expected to find a method that is more suitable for the characteristics of pension participants and the long-term needs ofThrough this analysis, it is expected to find a method that is more suitable for the characteristics of pension participants and the long-term needs of
UNEJUNEJ By capitalizing the role of shamans, indigenous peoples might still have opportunities to reclaim and defend their cultural rights. The article concludesBy capitalizing the role of shamans, indigenous peoples might still have opportunities to reclaim and defend their cultural rights. The article concludes
Useful /
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Namun, jika dilihat dari nilai Kewajiban Aktuarial, hasil perhitungan dengan kedua metode meningkat seiring usia peserta mendekati usia pensiun, meskipunNamun, jika dilihat dari nilai Kewajiban Aktuarial, hasil perhitungan dengan kedua metode meningkat seiring usia peserta mendekati usia pensiun, meskipun
UNEJUNEJ Minat komunitas internasional yang meningkat terhadap promosi hak asasi universal membuka kemungkinan bagi “penegakan berbasis kelompok atau model berbasisMinat komunitas internasional yang meningkat terhadap promosi hak asasi universal membuka kemungkinan bagi “penegakan berbasis kelompok atau model berbasis
USKUSK Pengajaran sastra juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, mendorong mereka untuk menyuarakan pendapat dan membangun kepercayaan diri.Pengajaran sastra juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, mendorong mereka untuk menyuarakan pendapat dan membangun kepercayaan diri.
USKUSK The results are expected to be useful for teachers and for students faced with writing a spoof. The population for this study was the third year studentsThe results are expected to be useful for teachers and for students faced with writing a spoof. The population for this study was the third year students